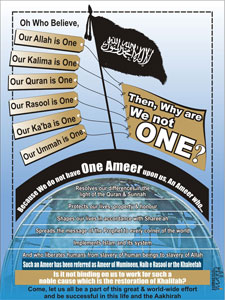Dalam pidato memperingati Hari Lahir Pancasila, Jumat lalu (1/6) Said
Aqil Siraj meminta agar tidak ada lagi wacana negara Islam di
Indonesia. Said bahkan meminta agar orang-orang yang masih menginginkan
membentuk negara Islam keluar dari Indonesia dan pergi ke Afghanistan.
“Tidak perlu lagi ada wacana negara Islam maupun kekerasan yang
mengatasnamakan Islam,” kata Said dalam pidato memperingati Hari Lahir
Pancasila 1 Juni 1945, Jumat (1/6).
Said Aqil juga menyatakan bahwa ideologi yang bertentangan dengan
ideologi bangsa Indonesia adalah subversif yang tidak boleh leluasa
hidup mengembangkan ajarannya dinegara Pancasila ini.
Mengherankan
Pernyataan itu jelas sesuatu yang mengherankan. Pernyataan itu
bertolak belakang dengan pandangan para imam madzhab, mujtahidin dan
para fuqoha. Mayoritas imam madzhab, mujtahidin dan fuqoha sepakat ihwal
kewajiban menegakkan khilafah. Hanya golongan sempalan yang
mengingkari kewajiban yang mulia ini. Apalagi jumhur ahlus sunnah telah
menyatakan kewajibannya. Berikut kami kutipkan sebagian kecil saja
perkataan para ulama salaf mengenai kewajiban menegakkan khilafah.
Al-’Allamah Abu Zakaria an-Nawawi, dari kalangan ulama mazhab Syafii,
mengatakan, “Para imam mazhab telah bersepakat, bahwa kaum Muslim wajib
mengangkat seorang khalifah.” (Imam an-Nawawi, Syarh Shahîh Muslim,
XII/205).
Ulama lain dari mazhab Syafii, Imam al-Mawardi, juga menyatakan,
“Menegakkan Imamah (Khilafah) di tengah-tengah umat merupakan kewajiban
yang didasarkan pada Ijmak Sahabat. (Imam al-Mawardi, Al-Ahkâm
as-Sulthâniyyah, hlm. 5).
Sungguh mengherankan bila ada seorang yang mengaku alim namun
mengingkari pendapat para ulama madzhab. Apalagi mereka yang mengaku-aku
sebagai ahlus sunnah wal jama’ah semestinya mengetahui bahwa perkara
ini adalah bagian dari ma’lumun min ad-din bi adl-dlarurah.
Perkara yang telah diketahui urgensitasnya. Para pecinta ahlus sunnah
seharusnya berada di garda terdepan dalam perjuangan penegakkan khilafah
dan syariat, karena para ulama ahlus sunnah memang telah mewajibkan hal
demikian.
Imam Ibnu Hazm mengatakan, “Mayoritas Ahlus-Sunnah, Murjiah, Syiah
dan Khawarij bersepakat mengenai kewajiban menegakkan Imamah (Khilafah).
Mereka juga bersepakat, bahwa umat Islam wajib menaati Imam/Khalifah
yang adil yang menegakkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka dan
memimpin mereka dengan hukum-hukum syariah yang dibawa Rasulullah saw.”
(Ibnu Hazm, Al-Fashl fî al-Milal wa al-Ahwâ’ wa an-Nihal, IV/87).
Demikian pula Imam Asy Syaukani dalam Nailul Authar jilid 8
hal. 265 menyatakan: “Menurut golongan Syiah, minoritas Mu’tazilah, dan
Asy A’riyah, (Khilafah) adalah wajib menurut syara’.” Ibnu Hazm dalam Al Fashl fil Milal Wal Ahwa’ Wan Nihal
juz 4 hal. 87 mengatakan: “Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah, seluruh
Murji`ah, seluruh Syi’ah, dan seluruh Khawarij, mengenai wajibnya Imamah
(Khilafah).”
Pernyataan di atas sekaligus menolak realitas bahwa khilafah
Islamiyyah dan penerapan syariat Islam telah lama hadir di Nusantara,
sebelum dihancurkan kolonial Kristen Portugis dan Belanda, lalu mereka
menggantikannya dengan sekulerisme dan demokrasi. Kesultanan Islam
seperti Sriwijaya Islam, Mataram Islam, Samudera Pasai hingga Jayakarta
yang diperintah oleh Fatahillah adalah realitas sejarah kegemilangan
Islam di tanah air.
Juga bagaimana para alim ulama rela menjadi martir syuhada melawan
penjajahan Barat yang menyebarkan sekulerisme dan misi zending Kristen
ke seantero Nusantara. Sosok Pangeran Diponegoro yang menobatkan dirinya
sebagai Sultan Abdulhamid Erucakra Sayidin Panatagama Khalifat
Rasulullah Sayidin Panatagama, menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin
yang berjiwa Islam dan memperjuangkan pelaksanaan syariat Islam melawan
VOC Belanda.
Sikap ini juga bertentangan dengan pendiri Nahdlatul Ulama KH Wahab
Hasbullah yang turut berpartisipasi dalam Kongres Khilafah pada bulan
Febuari 1926. Sayangnya acara tersebut disabotase oleh kolonial Inggris
melalui antek mereka Ibnu Saud, penguasa Hijaz.
Satu-satunya alasan mengapa muncul pernyataan yang kontradiksi dengan
pendapat para ulama salafush sholeh, adalah motif politik tidak terpuji
dari pembicara untuk mendiskreditkan ajaran Islam dan para pejuang
syariah. Motif ini adalah mata rantai imperialisme Barat terhadap dunia
Islam yang memanfaatkan sejumlah tokoh Islam dan politisi muslim untuk
melawan arus kebangkitan Islam.
Barat telah memahami sejak lama bahwa upaya menghancurkan Islam tidak
bisa dilakukan melalui jalur militer, akan tetapi harus dimulai dari
akar perjuangannya, yakni ajaran Islam. Maka bermunculanlah studi-studi
orientalisme yang bertujuan menghujamkan pisau beracun berupa perang
pemikiran dan peradaban terhadap kaum muslimin yang telah meninggalkan
dien mereka.
Di antara serangan berbahaya yang mereka lakukan adalah mendidik kaki
tangan mereka dari kalangan pemikir dan politisi muslim untuk
mengkampanyekan sekulerisme. Bila pemikiran sekulerisme dapat
diinduksikan ke dalam pemikiran umat, maka agama dan kehidupan akan
terpisah. Selanjutnya akan terjadi pemisahan agama dari negara dan
aturan politik. Berikutnya sistem kenegaraan dan sistem politik dunia
Islam akan digantikan dengan ajaran demokrasi yang memiliki beragam
derivatnya. Seperti di tanah air, pemikiran demokrasi disulap menjadi
demokrasi ala Indonesia sebagaimana ajaran sesat HAM pun dimodifikasi
agar dapat diterima oleh rakyat Indonesia.
Demokrasi memang mensyaratkan sekulerisme secara mutlak. Luthfie asy-Syaukanie dalam situsnya menulis artikel bertajuk Berkah Sekulerisme.
Di dalamnya terdapat pernyataan sebagai berikut, “Sebuah demokrasi yang
baik hanya bisa berjalan jika ia mampu menerapkan prinsip-prinsip
sekularisme dengan benar. Sebaliknya, demokrasi yang gagal atau buruk
adalah demokrasi yang tidak menjalankan prinsip-prinsip sekularisme
secara benar.”
Andaipun tidak disingkirkan, maka agama akan dipaksa untuk
ditafsirkan ulang agar sesuai dengan keinginan demokrasi. Seperti yang
ditulis Nader Hashemi seorang Asisten Profesor dalam bidang kajian Timur
Tengah dan Politik Islam, University of Denver. Dalam bukunya Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal
ia menyatakan bahwa “reinterpretasi ide-ide keagamaan menjadi amat
penting bagi kehidupan demokrasi liberal yang kondusif”. Apa yang
disampaikan Said Aqil hanyalah riak kecil dari gelombang westernisasi
dan depolitisasi Islam.
Pernyataan di atas bisa diniai bukan hanya depolitisasi Islam, tetapi
lebih dari itu bisa dinilai sebagai deislamisasi. Sayangnya pernyataan
seperti itu keluar dari lisan orang yang dianggap tokoh dan ulama.
Pernyataan demikian sangat berbahaya dan potensi daya rusaknya sangat
besar. Rasulullah saw memperingatkan dari keburukan yang berasal dari
ulama dan menyebutnya sebagai seburuk-buruk keburukan. Imam ad-Darimi
meriwayatkan dari al-Akhwas bin Hakim dari bapaknya :
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الشَّرِّ
فَقَالَ :« لاَ تَسْأَلُونِى عَنِ الشَّرِّ وَسَلُونِى عَنِ الْخَيْرِ ».
يَقُولُهَا ثَلاَثاً ، ثُمَّ قَالَ :« أَلاَ إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ
الْعُلَمَاءِ ، وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ »
Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw tentang keburukan.
Rasul bersabda: “jangan kamu tanya aku tentang keburukan dan tanyai aku
tentang kebaikan”. Beliau mengatakannya tiga klai. Kemudian beliau
bersabda: “ingatlah, sesungguhnya seburuk-seburuk keburukan adalah
keburukan ualam dan sesungguhnya sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan
ulama”.
Imam al-Ghazali di dalam Ihyâ’Ulûmuddîn menjelaskan: “ulama
itu ada tiga golongan. (Golongan) Ulama yang mencelakakan dirinya
sendiri dan orang lain, dan mereka adalah yang terang-terangan mencari
dunia dan mencurahkan perhatian terhadap dunia. Atau (golongan) ulama
yang membahagiakan dirinya dan orang lain. Mereka adalah yang menyeru
makhluk kepada Allah baik secara zahir maupun batin. Atau (golongan)
ulama yang mencelakakan dirinya sendiri tapi menyenangkan orang lain dan
dia adalah yang mengajak kepada akhirat dan bisa jadi ia menolak dunia
pada zahirnya sementara maksudnya pada batin adalah (mencari) penerimaan
makhluk dan mencari kedudukan. Maka perhatikan termasuk golongan
manakah kamu …”.
Imam al-Ghazali juga mengingatkan: ” … inilah jejak langkah para
ulama dan tradisi mereka dalam melakukan amar makruf nahi mungkar dan
minimnya atensi mereka kepada kekuasaan penguasa. Akan tetapi mereka
menyandarkan diri pada karunia Allah agar Allah menjaga mereka. Mereka
rela dengan keputusan Allah SWT agar Allah memberi mereka rezki
kesyahidan. Maka ketika mereka memurnikan niyat kepada Allah, ucapan
mereka pun membekas di dalam hati yang keras sehingga melunakkannya dan
menghilangkan kekerasan hati itu. Adapun sekarang, ketamakan telah
membelenggu lisan ulama sehingga mereka diam. Jika pun mereka
berbicara, perikeadaan mereka tidak bsia membantu ucapan mereka, maka
mereka pun tidak berhasil. Andai mereka benar (jujur) dan memaksudkan
hak ilmu niscaya mereka beruntung. Jadi rusaknya rakyat karena rusaknya
penguasa dan rusaknya penguasa adalah karena rusaknya ulama. Dan
rusaknya ulama adalah karena dikuasai cinta harta dan kedudukan. Siapa
saja yang dikuasai oleh kecintaan kepada dunia maka dia tidak akan mampu
meluruskan hal-hal yang remeh sekalipun, lalu bagaimana mungkin akan
bisa meluruskan para raja (penguasa) dan orang-orang besar. Dan Allah
adalah tempat meminta bantuan atas segala keadaan” (Ihyâ’ Ulûmuddîn, jus 7 hal 92).
Syaikh Abdul Aziz al-Badri, seorang ulama dari Baghdad yang syahid
dalam rangka amar makruf nahi mungkar kepada Saddam Husain, dalam
bukunya al-Islâm bayna al-‘Ulamâ wa al-Hukkâm hal 62
mengatakan: “disini harus dikatakan, bahwa standar dan timbangan untuk
mengetahui keberadaan seorang alim sebagai orang fasid atau shalih dan
keberadaan penguasa apakah seorang zalim atau adil, adalah Islam dan
bukan yang lain dan tidak ada yang lain yang bersama Islam.
Aktifitas ulama dan perbuatan penguasa, tindakan dan perilaku mereka
di dalam kehidupan dan terhadap masyarakat dan penentuan sikap sebagian
mereka kepada sebagian yang lain, semua itu ditimbang dengan timbangan
Islam dan distandarisasi dengan standar syara’. Maka sampai tingkat
maka mereka terikat kepada Islam dan menerapkannya, mengemban dakwahnya,
pemeliharaan mereka terhadap hukum-hukumnya dan pelayanan mereka kepada
para pengikut Islam maka setingkat itulah ia menjadi orang yang shalih
dan adil. Dan dengan sebaliknya tampaklah kerusakan mereka dan sejauh
mana mereka dituntun oleh kezaliman, meskipun orang ‘alim itu seorang
filsuf dan penguasa itu seorang yang jenius”. Wallâh a’lam bi
ash-shawâb. [Iwan Januar dan Yahya Abdurrahman - LS HTI]